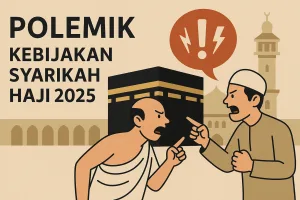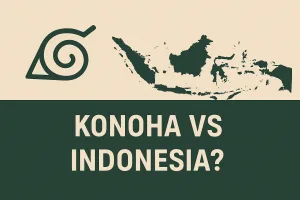![]()
Organisasi Masyarakat (ORMAS) adalah salah satu pilar penting dalam dinamika sosial Indonesia. Namun, banyak orang masih bingung membedakan ORMAS dengan paguyuban, perkumpulan, asosiasi, atau klub. Apa sebenarnya definisi ORMAS, bagaimana sejarahnya, dan apa perbedaannya dengan bentuk kelompok lain? Simak penjelasan lengkap berikut ini.
Definisi ORMAS Menurut Hukum Indonesia
Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ORMAS didefinisikan sebagai:
“Organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara.”
Ciri utama ORMAS:
-
Berbadan hukum atau tidak.
-
Bersifat sukarela dan non-profit.
-
Memiliki struktur kepengurusan jelas.
-
Fokus pada kegiatan sosial, agama, budaya, atau pemberdayaan masyarakat.
Contoh ORMAS terkenal: NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia), dan GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia).
Sumber hukum: UU No. 17 Tahun 2013 – JDIH Kemenkumham
Sejarah ORMAS di Indonesia
Era Kolonial (1900–1945)
ORMAS awal di Indonesia muncul sebagai respons terhadap penjajahan Belanda. Organisasi seperti Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1912) menjadi cikal bakal gerakan nasionalis. Tujuannya awalnya bersifat kultural dan edukatif, lalu berkembang ke politik.
Pasca Kemerdekaan (1945–1965)
ORMAS berperan aktif dalam mempertahankan kemerdekaan, seperti Laskar Hizbullah dan Barisan Pemuda Nasional. Setelah 1950, muncul organisasi berbasis agama dan ideologi, misalnya Nahdlatul Ulama (1926) dan PKI (Partai Komunis Indonesia).
Era Orde Baru (1966–1998)
Pemerintah membatasi ORMAS melalui UU No. 8 Tahun 1985, mewajibkan semua organisasi mengakui Pancasila sebagai asas tunggal. ORMAS seperti Pramuka dan Dharma Wanita didorong untuk mendukung program pemerintah.
Reformasi (1998–Sekarang)
Kebebasan berorganisasi dijamin UU. Muncul ORMAS baru seperti FPI (Front Pembela Islam) dan PA 212, meski beberapa menuai kontroversi.
Referensi sejarah: Buku “Sejarah Organisasi Masyarakat Indonesia” – Kemensos
Perbedaan ORMAS dengan Paguyuban, Perkumpulan, Asosiasi, dan Klub
Meski sama-sama kelompok sosial, istilah-istilah ini memiliki karakteristik unik:
1. ORMAS (Organisasi Masyarakat)
-
Ciri Khas:
-
Berbasis ideologi, agama, atau misi sosial.
-
Memiliki struktur legal (terdaftar di Kemenkumham).
-
Skala nasional atau regional.
-
-
Contoh: Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
2. Paguyuban (Gemeinschaft)
-
Ciri Khas:
-
Berdasarkan ikatan kekeluargaan atau kedaerahan.
-
Informal, tanpa struktur hierarkis ketat.
-
Tujuan utama menjaga tradisi dan solidaritas.
-
-
Contoh: Paguyuban Sunda, Paguyuban Warga Jawa di Kalimantan.
3. Perkumpulan (Vereniging)
-
Ciri Khas:
-
Dibentuk untuk tujuan spesifik (hobi, profesi).
-
Legalitas opsional (bisa berbadan hukum atau tidak).
-
Anggota terbatas dan homogen.
-
-
Contoh: Perkumpulan Filateli Indonesia, Klub Motor.
4. Asosiasi
-
Ciri Khas:
-
Berorientasi pada kepentingan profesional atau bisnis.
-
Memiliki standar keanggotaan ketat (misal: ijazah atau sertifikasi).
-
Fokus pada pengembangan kompetensi anggota.
-
-
Contoh: Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
5. Klub
-
Ciri Khas:
-
Bersifat rekreasi atau hobi.
-
Keanggotaan terbuka dan sukarela.
-
Tidak ada agenda politik atau sosial besar.
-
-
Contoh: Klub Sepak Bola, Klub Buku.
Persamaan ORMAS dengan Kelompok Lain
-
Sifat Sukarela: Keanggotaan tidak dipaksa.
-
Memiliki Tujuan Bersama: Meski skalanya berbeda.
-
Memperkuat Jaringan Sosial: Membangun relasi antaranggota.
Peran ORMAS dalam Masyarakat
-
Pemberdayaan Ekonomi: Pelatihan UMKM oleh NU atau Muhammadiyah.
-
Penjaga Nilai Budaya: Lembaga adat seperti Masyarakat Adat Dayak.
-
Kontrol Sosial-Politik: Advokasi kebijakan oleh Komnas Perempuan.
-
Bantuan Kemanusiaan: Respons bencana oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT).
Kontroversi ORMAS di Indonesia
Beberapa ORMAS dikritik karena:
-
Main Hakim Sendiri: Kasus sweeping oleh FPI (sebelum pembubaran 2020).
-
Politik Identitas: Eksklusivitas kelompok tertentu.
-
Penyalahgunaan Dana: Korupsi di tubuh organisasi.
Pemerintah kini memberlakukan sanksi tegas melalui Permenkumham No. 57 Tahun 2018 untuk ORMAS yang melanggar UU.
Regulasi: Permenkumham No. 57 Tahun 2018
Kesimpulan
ORMAS adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, tetapi perlu dibedakan dari paguyuban, asosiasi, atau klub yang memiliki tujuan lebih spesifik. Sejarah panjang ORMAS di Indonesia menunjukkan perannya sebagai agen perubahan sosial, meski tantangan seperti politisasi dan inkonsistensi regulasi tetap ada. Dengan memahami karakteristik masing-masing kelompok, masyarakat bisa memilih wadah organisasi yang sesuai kebutuhan.
Referensi: